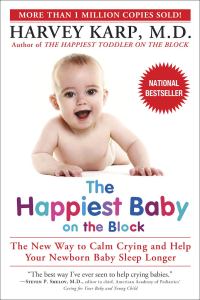Haloha, dapat notification dari wordpress kalau dua hari lalu blog saya sudah berusia 11 tahun. Wah tidak terasa yah! Seingat saya, tujuan menulis di dunia maya berawal saat saya memiliki cukup banyak waktu luang untuk menceritakan kegiatan-kegiatan yang saya jalani, seperti jalan-jalan. Ketika masih rajin naik turun gunung (sebulan bisa 2x dong!), saya selalu menuliskan catatan perjalan di blog ini, saat itu blog saya menjadi salah satu yang cukup hits pada masanya, dulu namanya gadisrantau.wordpress.com. Mayoritas tulisan saya di periode 2011 – 2015 adalah tentang gunung dan hutan, semua tentang jalan-jalan. Meskipun ada juga kisah pribadi yang senang dan sedih, hehe.
Pada tahun awal 2015, saya mengganti nama blog menjadi arsiyawenty.wordpress.com, awalnya sudah berniat untuk memakai domain sendiri. Namun, tujuh tahun berlalu, niat ini belum juga terealisasi. Alasan utamanya karena saya mulai tidak begitu aktif menulis, terutama setelah menyelesaikan studi dari Belanda dan kembali ke Indonesia. Minat saya menulis semakin menurun, kalau diperhatikan, sejak 2018 rata-rata saya hanya menghasilkan 1 atau 2 tulisan per tahun, wow! Penyebab utama karena saya sibuk mengerjakan urusan keluarga dan tidak memiliki waktu luang yang cukup untuk bisa menulis. Saya merasa main dengan anak jauh lebih penting dan dibutuhkan daripada meluapkan cerita dalam tulisan di dunia maya.
Namun, belakangan ini, tepatnya setelah membaca buku karya Robin Sharma (pertengahan 2022) yang berjudul The Monk Who Sold His Ferrari, saya mulai menulis lagi. Tetapi, kali ini saya menulis manual di buku harian, cerita tentang hari-hari dan rutinitas yang saya jalani. Sayangnya, komitmen menulis itu meredup di hari ke-20, sejak itu rasa malas kembali mengalahkan niat aktif menulis. Mungkin menulis rutinitas itu membosankan karena isinya ya itu lagi itu lagi. Ada baiknya saya menulis peristiwa yang menarik dan berbeda dari rutinitas harian saja, mungkin ya.
Oh ia, tulisan saya pernah juga bersifat lebih formal, dimuat dalam Harian Kompas, 1x di tahun 2021. Setelah itu, saya kembali vakum, hilang dari peredaran dan malas menulis. Mungkin juga, menulis itu tidak perlu dikategorikan atau dibatasi oleh topik, menulis saja apa yang ada dipikiran. Segera menulis ketika niat itu muncul, jangan menunggu sampai semangatnya tinggi, nanti redup dan malas lagi. Seperti tulisan ini misalnya, saya mengetik apa saja yang ada dipikiran, tanpa topik tanpa batas. Dan ini ini masih jam kerja. Saya beruntung karena selama pandemi (sejak Maret 2020) kantor tidak mewajibkan kehadiran fisik, jadi bisa bebas kerja dari rumah. Saya jadi tidak lelah di jalan dan punya banyak waktu untuk diri sendiri, seperti misalnya baca koran, baca buku, olahraga, dan berkebun.
Kondisi saya saat ini menyenangkan, kehidupan semakin berkualitas. Perubahan yang besar terjadi dari cara saya memaknai kehidupan dari yang sepele sampai yang cukup berat. Mentalitas saya semakin dewasa, meskipun masih sering ada celah egoisnya juga. Saya sudah bisa mengontrol emosi negatif dengan memberi waktu lebih besar untuk pikiran positif. Saya jadi lebih dewasa dan kurang egois, karena saya menyadari atau lebih tepatnya tersadar oleh keadaan kalau saya tuh dulu egois banget yah! haha everybody is changing.
Sejak pertengahan 2019 sampai hari ini, saya tinggal di Bandung Coret, loh kok? Ia karena lokasinya sudah di perbatasan antara Kota Bandung dan Kabupaten Soreang, di Taman Kopo Indah. Belakangan ini saya bersyukur bisa tinggal di TKI, soalnya kita punya Tol Margaasih Timur. Bisa terbebas dari macet, meskipun biaya tolnya mahal. Keputusan untuk beli mobil di akhir tahun 2021 menjadi tipping point meningkatnya kebahagian saya. Ternyata kendaraan ini memudahkan saya kemana-mana, saya bisa ke kantor dengan nyaman, bisa main bareng keluarga dalam kondisi cuaca apapun, hujan panas bisa jalan, bebas hambatan.
Keputusan untuk beli mobil tercetus begitu saja, awalnya karena waktu itu saya, suami, dan anak kehujanan pulang dari Lembang Park Zoo. Waktu itu kita naik motor, saya kesal sekali dan langsung semangat bongkar tabungan untuk beli mobil. Dan ternyata keputusan itu tepat, lelah juga berhemat dan selalu menabung tapi menggerutu setiap mau keluar rumah, karena panas atau hujan. Apakah ini kebutuhan atau keinginan, saya tidak begitu berfikir panjang saat itu. Setelah punya mobil, saya jadi bisa mulai main basket lagi, lokasinya jauh sih di Bandung Utara, tetapi karena ada akses tol, semua jadi mudah dan lancar. Selain itu, kami sekeluarga jadi bisa menikmati hidup, terutama karena jadi mudah untuk kemana saja.
Nah, saya juga punya sepeda, lumayan bisa keliling komplek cari keringat dan kontemplasi, cari inspirasi. Olahraga itu bermanfaat sekali, terutama untuk me-refresh pikiran, badan lebih bugar, kulit lebih halus dan cerah, banyak deh manfaatnya. Dalam seminggu, saya bisa lari, berenang, main sepeda, dan basket. Aktivitas ini membantu saya untuk merasa lebih rileks dan bahagia. Saya mengerjakan ini saat anak sedang sekolah dan sebelum jam kerja, pagi hari sebelum jam 10.00 WIB.
Panjang juga nih tulisan kali ini, plotnya juga tidak teratur, tidak dibatasi topik, ketik semua yang ada di pikiran. Mungkin sudah saatnya kembali aktif menulis di dunia maya ya, segera menulis ketika ingin dan tidak perlu banyak rencana, jalanin aja gitu yah. Terima kasih wordpress sudah memberikan ruang untuk menuliskan kelana hidup yang kalau dibaca ulang seru juga. I am back!